Kenapa “Malas” Dilabeli Negatif?
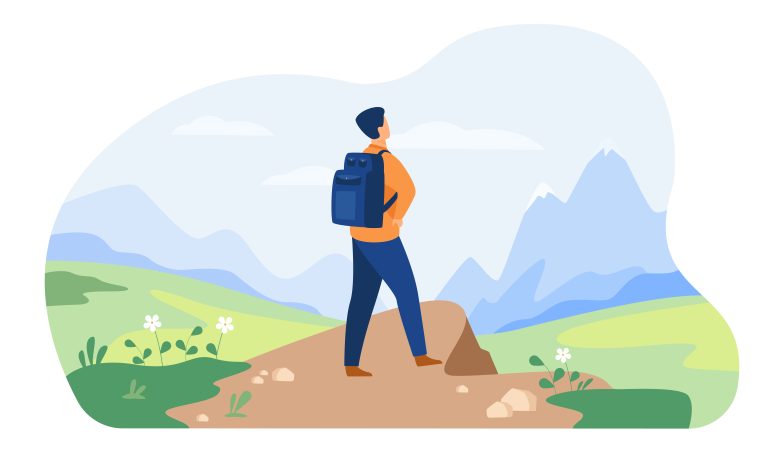
Oleh: Angga Putra Mahardika
Mahasiswa KPI UIN SSC
Peristiwa malasnya mahasiswa sering dicap negatif. Tidak mengerjakan tugas, dicap malas. Datang terlambat, manajemen waktu buruk, tandanya malas. Nilai kecil, tidak rajin belajar, artinya malas. Abstain, apalagi. Sebenarnya, kenapa orang disebut malas? Tetapi, benarkah semua itu mencerminkan kemalasan sejati? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat lebih dalam bagaimana makna “malas” dibentuk dalam manusia.
Malas biasanya penghakiman seseorang, bukan dari diri sendiri. Ketika ada yang menghambat, dibilang malas. Ketika hasil kurang maksimal, dinilai malas. Malas seringkali diberikan bukan diakui. Pemberian gelar malas, bisa karena kita tidak memahami orang lain. Tidak empati, tidak simpati. Hal ini mengkritik asumsi manusia sebagai sarana, bukan tujuan. Ketika kita memberi label tanpa memahami, kita menempatkan manusia sebagai alat ukur prestasi, bukan sebagai individu yang utuh. Karena itu, penting mempertanyakan: siapa yang sebenarnya berhak menyebut orang lain malas?
Orang yang menghakimi terkadang merasa tidak malas. Malas dikeluarkan oleh si “rajin” kepada si “malas”. Supaya tidak main hakim sendiri, istilah itu harus datang dari mulut manusia sendiri. Itu baru malas sejati. Orang yang kita katakan malas, mereka punya kegiatan lain, yang lebih penting. Orang malas itu, mereka punya keterbatasan, yang tentu bukan keinginan mereka sendiri.
Secara arete, tidak ada manusia yang ingin malas. Sebab salah satu musuh utama manusia itu bosan. Jika mahasiswa malas, tentu bosan, dan mendorong rasa produktif. Semua manusia itu produktif, bedanya apa hal yang mereka kerjakan. Sudah sesuai dengan tanggung jawab atau belum. Kalau belum, artinya ada tanggung jawab lain yang lebih utama. Selain dari sudut pandang etika kebajikan, kita juga bisa melihat fenomena ini dari sudut biologis—bagaimana otak manusia dirancang untuk bertahan dalam kondisi tekanan.
Secara biologis, manusia punya otak reptil. Otak yang berfungsi untuk menjaga manusia supaya bertahan hidup. Bisa jadi orang malas itu sedang bertahan hidup dengan caranya sendiri. Ada manusia yang tidak malas, besoknya gantung diri. Ada manusia yang ceria dan aktif, namun malamnya menenggak sianida. Apakah para buddhis yang bersemedi bertahun-tahun itu, berdiam diri itu, tidak disebut malas?
Malas. Cara bertahan hidup dari absurd nya dunia. Masalah struktural, problem kultural, masalah institusional. Masalah-masalah yang bukan ada sebab keinginan manusia sendiri. Masalah itu ada sebab orang lain. Sebagaimana manusia, kadang tidak bisa menolak. Kita tidak bisa lari dari utang negara. Kita menghadapinya, membayar pajak. Kita tidak bisa lari dari pejabat korup. Kita bertanggung jawab memilih pejabat lain yang “barangkali” lebih baik. Malas adalah kondisi ketidakberdayaan seseorang untuk bereaksi dan merespon kondisi atau sesuatu. Dalam konteks tekanan struktural semacam itu, “kemalasan” bisa dimaknai ulang sebagai reaksi terhadap ketidakberdayaan yang terus-menerus dipaksakan.
Penulis punya teman yang sering dilabeli malas oleh teman lain. Sebut saja inisial D asal Jakarta. Bukan tanpa alasan, karena si D ini diperkirakan lebih berada daripada mahasiswa lain. Dia lumayan kaya, kos elite, makan sesuai keinginan, hape bagus, sering top up game, transferan oke, sering modif motor. Wajar orang lain mengatakannya hedon. Dengan apa yang sudah disebutkan, si D masih kesulitan mengerjakan tugas, terutama kelompok. Tidak jarang banyak mahasiswa lain yang menghindari sekelompok dengannya.
Si D ini kesusahan menyesuaikan minat dan bakatnya. Dia berbakat menulis, tetapi tidak konsisten. Dia berbakat videografi, namun jarang upload video. Sebenarnya dia sendiri juga bingung, bagaimana minat dan bakatnya ini tersalurkan. Hobi dia bermain game, dilingkungan yang kurang tepat bermain game bisa mengacu tindakan kurang dewasa. Dalam pandangan ini, main game bisa menjadi pelepas stress dan penatnya. Apa salahnya kita menghibur diri?
Tapi lagi-lagi, teman lain sangat sulit berkompromi dengan dia. Karena si D ini anak tunggal. Dia biasa dimanjakan orang tuanya, punya uang berlebih, dan sepertinya tidak pernah diberi parenting tegas oleh orang tua. Sudah jelas dan sah si D ini berada di kondisi yang tidak ia inginkan. Dia tidak bisa menentukan punya saudara atau tidak. Dia tidak bisa menentukan bagaimana dia dididik. Yang akhirnya semua itu menyebabkan kebingungan. Kebingungan membuatnya stagnan, berproses lebih lambat.
Si D ini masih remaja transisi dewasa. Tentu dia masih perlu adaptasi, dalam situasi ini dia merantau. Yang setiap hari dilayani orang tua, sekarang apa-apa sendiri. Dia pasti cultur shock dengan kebiasaan, daerah, dan bahasa baru di Kota Cirebon.
Sebagian dari kita memiliki orang “malas” seperti D ini. Kembali lagi pada apa yang sudah disampaikan di atas. Apakah si D ini malas? Atau dia hanya kesulitan berkembang di dunia baru. Apakah si D ini malas? Atau dia hanya tidak bisa menjawab ekspetasi banyak orang. Rajin yang diagungkan, Bill Gates, Mark Zuckerberg, apakah rajin itu bertaraf kesuksesan? Apa selama ini kita hanya membuat-buat kata “malas” untuk merendahkan orang lain supaya kita merasa lebih baik?
Mungkin kita sedikit lebih beruntung dari dia. Kita bukan orang kaya, tetapi didikan orang tua yang mendewasakan. Kita tidak serba ada, tetapi kita berusaha cukup atas apa yang ada. Kita pernah malas di bidang yang tidak kita kuasai. Sesungguhnya kita bukan malas, betul? Kita hanya tidak tahu harus merespon bagaimana. Kita dalam kondisi yang asing dan mencoba beradaptasi.
Jangan-jangan efek media sosial macam; validasi, standar tiktok, pamer prestasi. Yang membuat kita berani mengatakan kata “malas” pada orang lain. Bisa saja kita yang malas memahami dan minta dipahami. Kita yang malas mengerti dan selalu ingin dimengerti. Jangan-jangan kita lah pelaku dari fenomena “malas” ini?
Kita semua pernah malas. Malas yang kita lakukan tidak salah. Malas hanya proses bertahan hidup yang salah dimaknai. Malas adalah bagian dari kita.***






