Spasi: Dari Kekeliruan Linguistik menuju Kesadaran Filosofis
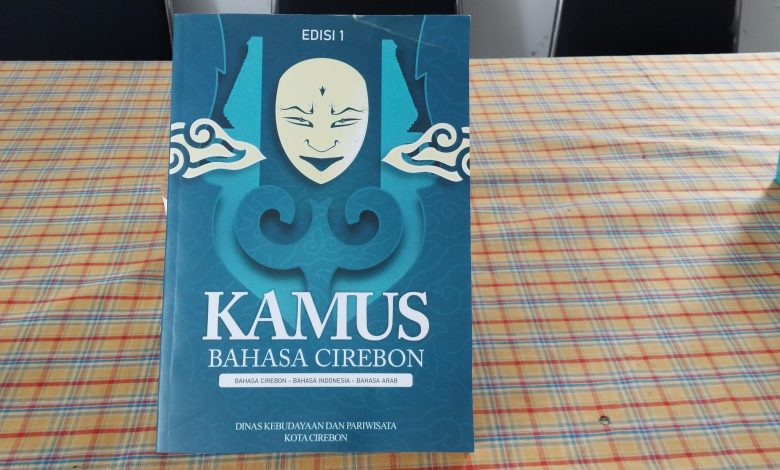
Oleh: Syarifuddin
Pengamat Praktik Komunikasi Publik
Saya lupa tanggal pastinya. Seingat saya pada 7 Agustus 2021 pada live Instagram bertajuk #MalamMingguanTempo bersama Goenawan Mohamad (GM), ada sebuah perbincangan sekaligus pernyataan menarik sepanjang sesi. Salah satunya, GM menjelaskan bahwa bahasa bisa dibedakan menjadi dua, yakni bahasa sebagai komunikasi dan bahasa sebagai ekspresi. Bahasa sebagai komunikasi maksudnya penggunaan bahasa yang mengikuti konvensi dan aturan. Sementara itu, bahasa sebagai ekspresi mengikuti apa yang ada di dalam bahasa tersebut. “Saya harap kita tetap memelihara bahasa konvensi, tetapi jangan mematikan bahasa sebagai ekspresi,” kata GM.
Butuh sekian waktu yang relatif panjang untuk saya mengamati bagaimana konsistensi kita dalam mempraktikkan apa yang disebut GM sebagai “memelihara bahasa konvensi” dalam praktik berbahasa sehari-hari. Ya, konsistensi menjadi sesuatu yang sangat sulit apalagi dalam penggunaan bahasa yang lebih mengutamakan “biasanya”, “kayaknya lebih enak begini deh”, dan beragam alasan subjektif lainnya. Kasus yang saya amati sekian lama adalah konvensi terkait penulisan Iduladha, Idulfitri, sub-, antar-, dan bentuk terikat lainnya. Sebab, masih banyak yang meyakini bahwa perlu ada spasi pada bentukan kata tersebut.
Faktanya, kita memang masih berkutat dengan keinginan untuk selalu menempatkan spasi pada sebuah kata yang berdasarkan konvensi dan aturan linguistik sebetulnya merupakan sebuah kata utuh. Secara ortografis, kata didefinisikan sebagai unit-unit tertulis yang dibatasi oleh spasi-spasi. Unit tersebut disebut ortographic word atau kata ortografi yang kemudian disebut word form atau bentuk kata. Oleh sebab itu, kalau ada kalimat aku cinta kamu, kita akan dengan cermat menyatakan bahwa kalimat tersebut terdiri atas tiga kata dengan melihat elemen pemisah (spasi) di antara setiap kata.
Oleh sebab itu, kekacauan logika bahasa dalam menempatkan spasi pada sebuah kata yang seharusnya utuh, misalnya subbagian yang ditulis sub bagian, hanya akan menimbulkan inkonsistensi linguistik. Praktik itu justru tidak dianggap sebagai sebuah masalah besar. Padahal, kalau meminjam hukum propaganda ala mantan Kanselir Jerman, Joseph Goebbels, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai efek ilusi kebenaran (fenomena timbulnya kecenderungan untuk percaya pada informasi yang salah sebagai suatu kebenaran, setelah adanya proses repetisi atau pengulangan). Kalau benar itu yang terjadi, sepatutnya kita gelisah pada efektivitas ragam upaya pemartabatan bahasa Indonesia.
Mari kita urai kerumitan atas kekeliruan cara kita selama ini berbahasa dengan berusaha mengikat ulang pemahaman kita tentang apa yang dinamai bentuk terikat. Ya, salah satu kesalahan yang lazim ditemukan adalah aspek morfologi (bentuk kata) yang menyebabkan kita keliru menempatkan spasi. Kekeliruan yang dimaksud merujuk pada (1) perbedaan antara aturan tata bahasa dan praktik penulisan bentuk terikat dan (2) perbedaan penulisan bentuk terikat (ada yang mengikuti tata bahasa dan ada yang tidak mengikuti tata bahasa). Padahal, apabila merujuk konvensi dan pedoman tata bahasa, penggunaannya harusnya seragam.
Bentuk terikat merupakan bentuk yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak memiliki arti apabila tidak melekat pada kata dasar. Nah, agaknya kekeliruan ihwal pemberian spasi yang terjadi patut diduga disebabkan oleh anggapan bahwa bentuk terikat adalah sebuah kata. Padahal, oleh para ahli, bentuk terikat yang melekat pada kata dasar telah digolongkan sebagai prefiks atau awalan, sehingga penulisannya disambungkan dengan kata dasar.
Di sisi lain, kita kadung mengganggap bahwa tata bahasa melulu tentang penyusunan kalimat. Padahal, tata bahasa (grammar) berfokus pada struktur. Struktur, dalam linguistik, merentang dari struktur bunyi, struktur kata, struktur kalimat, sampai struktur makna. Struktur kata agaknya luput dalam wacana umum penyusunan sebuah produk bahasa. Fokus perhatian terbagi lebih besar kepada struktur kalimat, format naskah, dan substansi (konten) yang disampaikan. Padahal, sebuah praktik berbahasa (lisan atau tulisan) mensyaratkan kepaduan antarelemen untuk tersampaikannya sebuah pesan atau makna secara lebih efektif.
Berdasarkan pengamatan pribadi, setidaknya ada lima bentuk terikat yang penulisannya dikelirukan oleh penambahan spasi. Lima bentuk terikat yang dimaksud adalah sub-, antar-, anti-, non-, dan pasca-. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa kekeliruan yang dimaksud adalah praktik penulisan bentuk terikat yang tidak taat asas. Asas linguistik dan tata bahasa mensyaratkan penulisan bentuk terikat harus digabung tetapi pada praktik yang ditemukan justru masih ditemukan penulisan bentuk terikat yang dipisahkan (oleh spasi) dari kata dasar.
Bentuk terikat sub- memiliki arti bawah, agak, dan dekat. Pada sampel yang ada, penulisan sub- justru dipisah dari kata dasar, misalnya sub bagian. Cara paling sederhana untuk menyatakan bahwa sebuah entri pada kamus berstatus sebagai kata tunggal (yang dalam penggunaannya dapat dipisah dari kata lain) adalah mengecek definisi entri tersebut di kamus. Bagian, pada konteks ini, memiliki definisi sebagai cabang dari suatu pekerjaan. Sementara itu, sub tidak memiliki definisi apapun, kecuali apabila kita mencari entri sub-. Tanda (-) adalah fitur penanda bahwa entri tersebut berstatus sebagai bentuk terikat. Oleh sebab itu, apabila ingin taat asas, seharusnya tertulis subbagian (yang artinya ‘di bawah bagian’) bukan sub bagian.
Inkonsistensi penulisan bentuk terikat selanjutnya adalah antar-. Sebagai contoh, cukup sering ditemukan penulisan bentuk terikat tersebut menjadi antar lembaga. Apabila penulisan antar dipisah dari kata dasar, maka kata tersebut menjadi verba (kata kerja) dengan arti bawa atau kirim. Tentu saja, hal ini akan mengacaukan maksud dari frasa yang ingin dibuat. Makna yang ingin dicapai dari penulisan antar lembaga tentu saja adalah ‘dalam lingkungan atau hubungan yang satu dengan yang lain’ tetapi eksekusi penulisannya salah. Seharusnya, antar- diperlakukan sebagai bentuk terikat dan dituliskan menjadi antarlembaga.
Isu selanjutnya mengenai penulisan bentuk terikat anti-. Contoh penulisan yang tidak konsisten dapat ditemukan pada penulisan anti korupsi. Entri anti memang memiliki makna tidak setuju, tidak suka, dan tidak senang. Referensi makna ini dimiliki oleh anti sebagai sebuah partikel pada struktur kalimat. Oleh sebab itu, dalam penggunaannya, anti memerlukan semacam preposisi (kata depan) yang selalu berada di depan kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Contoh kalimatnya adalah Dedi Mulyadi sangat anti terhadap rencana itu.
Sementara itu, apabila anti ingin dihadapkan langsung pada nomina (kata benda) yang merujuk pada makna melawan, menetang, dan memusuhi, maka anti- harus diperlakukan sebagai bentuk terikat. Oleh sebab itu, penulisannya tidak boleh dipisah dengan kata dasar yang diikutinya. Pada sampel yang ada, penulisan anti korupsi jelas keliru. Seharusnya, frasa tersebut ditulis menjadi antikorupsi.
Bentuk terikat selanjutnya adalah non-. Penulisan yang inkonsisten ditemukan pada frasa lembaga non struktural. Apabila non ditulis terpisah, maka non adalah kata yang dapat berdiri sendiri. Padahal, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hanya memaknai non sebagai kependekan dari nona, istilah dalam agama katolik sebagai biarawati, dan kaum non yang merupakan kumpulan orang yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah (Belanda) pada zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia. Apabila maksud yang ingin dicapai adalah non- yang memiliki arti tidak, bukan, dan tanpa, maka non- harus diperlakukan sebagai bentuk terikat dengan dituliskan menjadi lembaga nonstruktural.
Selanjutnya, sepanjang hari di tanggal 6 Juni 2025, saya berusaha melakukan riset seadanya dengan mengamati bagaimana media sosial dan takarir (caption) yang melengkapi unggahan menampilkan penulisan Iduladha. Saya ingin memulai dari sebuah kisah sederhana. Begini kisahnya.
Suatu hari, teman saya yang bekerja di sebuah toko memasang pengumuman yang telah dibuat oleh bosnya bertuliskan “Harga asli Rp2.500.000, sekarang hanya Rp250.000!” Lalu, ada yang menghampiri dan tertarik untuk membeli. “Saya beli,” ucap seseorang seraya memberikan uang dengan jumlah Rp250.000. Si bos kaget. Ternyata, dia salah ketik—seharusnya Rp2.500.000 menjadi Rp2.250.000, bukan Rp250.000. Si calon pembeli kecewa? Pasti. Si bos? Tentu saja lega.
Ya, kurang lebih begitu. Dalam hal uang, kesalahan sekecil apa pun langsung disadari dan dikoreksi. Namun, ketika seseorang menulis Idul Fitri/Adha, Iedul Fitri/Adha, atau bahkan Id Fitri/Adha, banyak yang menerimanya begitu saja tanpa berpikir ulang. Padahal, seperti halnya angka dalam transaksi, kesalahan dalam bahasa pun seharusnya tidak diabaikan. Jika dibiarkan terus-menerus, lama-kelamaan kita akan menganggap yang salah sebagai sesuatu yang wajar—dan itulah awal dari kekeliruan yang lebih besar.
Mungkin memang sebegitu sulitnya untuk bicara soal ketegasan dalam “memelihara bahasa konvensi”. Mungkin, kita bisa berdebat seharian tentang pentingnya tanda baca dalam teks hukum atau pengaruh pemenggalan kata dalam puisi, tetapi ketika menyangkut penulisan Idulfitri atau Iduladha, kita seakan memasuki wilayah tanpa hukum, di mana siapa pun boleh menulis sesuka hati. Padahal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sebagai sebuah hasil konvensi, penulisan yang benar adalah Idulfitri dan Iduladha—satu kata, tanpa spasi, tanpa variasi eksotis ala kuliner fusion.
Penulisan Idulfitri digabung karena memiliki arti hari raya berbuka yang terdiri atas unsur “id” dan alfitri. Pada posisi awal menggunakan tanda harakat “u” (damah), sehingga menjadi idu l-fitri. Dengan demikian penulisan “Idul Fitri” tidak benar karena (u)l seharusnya melekat pada kata “fitri” sebagai tanda makrifah, al-fitri. Maka dari itu, “idul” menjadi unsur terikat yang harus bergabung dengan kata sesudahnya.
Selain itu, kekeliruan juga sering dijumpai pada kalimat “Selamat Hari Raya Idul Fitri” Dalam kalimat tersebut ada dua hal yang kurang tepat yaitu penulisan “Hari Raya” dan “Idul Fitri”. Kesalahan tersebut karena memiliki arti ganda, “id” pada kata idul berarti hari raya, sehingga cukup ditulis “Selamat Idulfitri” yang berarti Selamat Hari Raya Fitri.
Selanjutnya, penulisan Idul Adha yang dipisah adalah bentuk tidak baku. Secara etimologi, asal usul kata Iduladha berasal dari bahasa Arab. Dari (عِيْدٌ) ‘īd yang artinya ‘perayaan’ dari kata (عَادَ) ‘āda yang artinya ‘kembali; mengunjungi’ dan dari kata (اَلْأَضْحَى) al-aḍḥā yang artinya ‘kambing sembelihan’ dari kata (اَضْحَاةٌ) aḍḥāh yang artinya ‘kambing sembelihan’ dari kata (ضَحَّى) ḍaḥḥā yang artinya ‘menggembala kambing pada waktu duha; menjamu pada waktu duha; menyembelih kambing saat Iduladha’ dari kata (ضَحَى) ḍaḥā yang artinya ‘memasuki waktu tengah hari’.
Salah kaprah ini mirip dengan pihak yang ngotot menyebut ‘jamaah’ padahal yang dimaksud ‘jemaah’, atau orang yang menulis ‘handal’ ketika maksudnya ‘andal’. Mungkin tidak sepenting salah menulis jumlah angka dalam rekening transfer, tetapi tetap saja, ini soal ketepatan dalam berbahasa. Selalu ada saja yang akan berkilah, “Ah, yang penting maksudnya sampai!” Bukankah bahasa adalah medium komunikasi yang harus digunakan dengan cermat? Jika kita tidak mempermasalahkan Idul Fitri dan Idul Adha, lalu apa selanjutnya? Terima kasih menjadi terimakasih ? Garuda Pancasila menjadi Garuda Panca Sila? Sedikit demi sedikit, kita akan menjadi pihak yang membuka pintu bagi kekacauan linguistik.
Yang jauh lebih memprihatinkan adalah ketika kekeliruan semacam ini justru datang dari institusi pemerintah. Setiap tahun, baliho besar, spanduk, hingga unggahan resmi dari pemerintah dengan percaya diri menulis “Selamat Idul Fitri” atau “Selamat Idul Adha”. Namun, pengamatan saya pada beberapa unggahan media sosial di kementerian rata-rata sudah dengan akurasi bahasa Indonesia yang tepat; tanpa spasi untuk Idulfitri dan Iduladha.
Namun, yang keliru juga masih banyak. Padahal, merekalah yang seharusnya menjadi panutan dalam praktik komunikasi publik yang berkelas dan berstandar. Ironisnya, alih-alih menjadi penjaga gawang kebahasaan, mereka malah ikut menyuburkan kesalahan yang sama, dari tahun ke tahun, seolah-olah sudah disahkan secara institusional. Bayangkan jika Bank Indonesia teledor menulis angka pada lembar rupiah, atau jika Kementerian Hukum keliru dalam redaksi pasal undang-undang, tentu akan menimbulkan kegaduhan. Maka, timbul pertanyaan: kenapa kesalahan berbahasa, yang sejatinya menyangkut identitas nasional, dibiarkan berlalu tanpa koreksi? Kalau urusan warna logo saja bisa diperlakukan dengan penuh kehati-hatian, mengapa dua kata yang mestinya menyatu ini tak diberi perhatian serupa?
Sudah saatnya kita memperlakukan bahasa kita seperti kita memperlakukan nama kita sendiri. Sebagaimana kita ingin nama kita diucapkan dengan benar—tanpa dipelintir seenaknya—begitu pula hendaknya kita memberi hormat pada bahasa Indonesia: dengan merawat ketepatan, bukan mengabaikannya.
Dalam linguistik, spasi bukan hanya ruang kosong di antara kata-kata. Ia adalah instrumen penting dalam pemaknaan. Tanpa spasi, kata-kata kehilangan kejelasan struktur. Ambil contoh sederhana: “kita makan sekarang” berbeda maknanya dari “kita makan, sekarang”. Dalam versi pertama, perintah muncul tanpa ragu. Di versi kedua, kehadiran koma—yang berfungsi seperti jeda—mengubah nada dan intensitas pernyataan. Spasi, koma, titik, dan bentuk jeda linguistik lainnya adalah alat untuk memberi struktur pada bahasa tulis, agar dapat dibaca, dipahami, dan ditafsirkan sebagaimana mestinya.
Kesalahan yang kerap kita temui, seperti penulisan “Selamat Idul Fitri” secara terpisah, menunjukkan ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap aturan dasar ini. Padahal, menurut kaidah kebahasaan, frasa tersebut adalah satuan idiomatis yang tidak bisa dipisahkan. Penulisan yang keliru tidak hanya menunjukkan keteledoran teknis, tetapi juga mempengaruhi makna dan keutuhan pesan. Dan ketika kekeliruan ini dilakukan oleh lembaga negara—lembaga yang memiliki otoritas dalam pendidikan dan komunikasi publik—dampaknya tidak kecil. Ia memperkuat kelaziman kesalahan, menciptakan preseden yang salah, dan membuat kekeliruan tampak seolah benar.
Jika kita tarik ke dalam kerangka filsafat, kesalahan memahami spasi ini mencerminkan kegagalan memahami peran jeda dalam berpikir dan berkomunikasi. Dalam banyak tradisi filsafat, jeda bukanlah kehampaan yang tidak bermakna. Dalam dialog Plato, misalnya, jeda antarucapan bukan cuma waktu hening, tapi ruang bagi berpikir. Begitu pula dalam filsafat Timur seperti Zen, keheningan bukan akhir percakapan, melainkan bagian penting dari pemahaman. Jeda memberi kita waktu untuk mencerna, mempertimbangkan, bahkan meragukan sebelum melanjutkan atau merespons.
Dalam praktik sehari-hari, kita tahu betapa pentingnya jeda itu. Seorang orator yang piawai tahu kapan harus berhenti sejenak sebelum menyampaikan kalimat penting—sebuah teknik retoris yang memancing perhatian. Di dunia jurnalistik, penempatan kutipan langsung tanpa konteks atau jeda naratif bisa menyesatkan pembaca. Bahkan dalam komunikasi digital, kesalahan meletakkan spasi atau titik bisa mengubah makna pesan secara drastis. Misalnya, “jangan dihukum yang bersalah” bisa berarti dua hal berbeda tergantung di mana jedanya dipahami.
Kesadaran terhadap spasi dan jeda adalah kesadaran terhadap struktur dan makna. Ia menunjukkan kemampuan membedakan mana yang harus dipisah, dan mana yang harus disatukan. Di balik kemampuan teknis ini, ada sikap epistemologis: bahwa kita tidak sekadar menyalurkan informasi, tetapi juga membentuk cara orang memahami dunia melalui bahasa.
Sayangnya, dalam praktik birokrasi atau komunikasi publik di Indonesia, hal-hal seperti ini kerap dianggap sepele. Bahasa diperlakukan sebagai pelengkap administratif belaka, bukan sebagai instrumen utama representasi publik. Ketika spanduk resmi dari pemerintah menampilkan kesalahan dasar dalam bahasa, itu bukan semata-mata soal tata tulis. Itu cermin dari bagaimana kita memandang peran bahasa dalam masyarakat—apakah ia dihormati, atau hanya digunakan asal-asalan.
Jika pemerintah bisa sangat cermat dalam menyusun nomenklatur lembaga, protokol acara, atau estetika visual logo, mengapa perhatian yang sama tidak diberikan pada aspek kebahasaan? Apakah bahasa dianggap kurang penting dari simbol dan warna? Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh para pengelola komunikasi publik.
Dengan memahami spasi sebagai bagian dari sistem makna, dan jeda sebagai bagian dari proses berpikir, kita sebenarnya sedang menegaskan satu hal: tidak semua yang diam itu kosong. Ada nilai dalam diam. Ada fungsi dalam jeda dan ada makna dalam spasi. Kita hanya perlu lebih peka dan lebih peduli.***






